
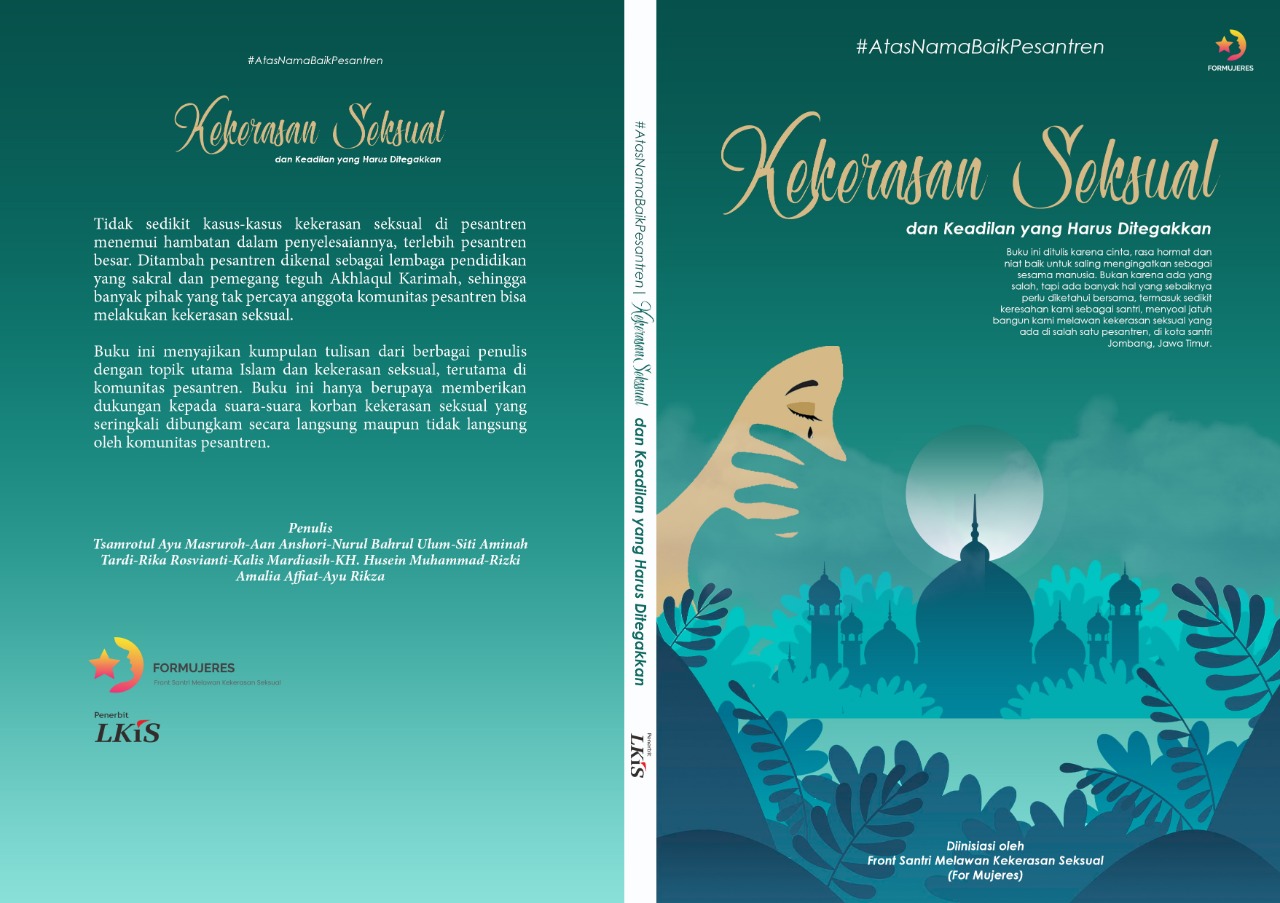
Oleh Aan Anshori
Sebagai orang Islam, Sunni, saya rutin mengucap janji suci kepada Gusti. Minimal lima kali saat shalat. Saya berjanji; seluruh hidup, ibadah, bahkan kematian saya persembahan hanya untukNya semata. Bukan yang-lain. Gusti meminta kita menjadi rahmat bagi alam raya. Kita diminta olehNya, tidak hanya berbuat adil, namun juga memperlakukan orang secara lebih baik. Jika ada problem ketidakadilan, kita diminta tidak boleh tinggal diam. Doktrin dalam Islam mewajibkan kita mengubah ketidakadilan tersebut, bahkan dengan tindakan paling minimalis sekalipun; mengutuknya dalam hati. Dalam persoalan kekerasan seksual yang melibatkan institusi pendidikan paling sakral di lingkungan Sunni Indonesia, pesantren, kita seperti ditantang untuk membuktikan janji kita pada Gusti; janji yang bisa jadi sulit ditepati.
KEKERASAN SEKSUAL; PESANTREN DAN KERIKUHAN
Kekerasan seksual yang melibatkan pesantren sudah jamak terjadi, meskipun publik masih merasa rikuh membicarakannya. Hal ini dikarenakan, salah satunya, pesantren dianggap sangat dekat dengan kultur dan sistem yang dimiliki Nahdlatul Ulama (NU). Bisa dikatakan, secara politik organisasi Islam terbesar di Indonesia merupakan anak paling disayang oleh negara ketimbang anak-anak yang lain –baik di internal kelompok Islam maupun non-Islam. Saat negara ini terseok-seok menghadapi salah satu kekuatan radikalisme Islam (FPI, HTI dan kroni-kroninya), NU dan kekuatan yang ia miliki berperan sangat aktif. Peran ini secara tidak langsung memengaruhi cara pandang kelompok kritis masyarakat sipil Indonesia terhadap NU, dan juga pesantren yang ia miliki.
Dalam konteks kekerasan seksual di pesantren, saya merasakan, ada kesan kuat di masyarakat sipil dan birokrasi; bertindak tegas terhadap problem yang terkait pesantren bukanlah hal yang mudah. Di Jombang misalnya, di mana NU dan pesantren dianggap memiliki kekuatan politik sangat di kabupaten ini, saya mengetahui sendiri betapa tidak mudah bagi aparat penegak hukum untuk menuntaskan sebuah kasus yang melibatkan pesantren.
Setidaknya ada empat kasus yang sangat terasa kuat memberikan privilege kepada; kasus tabrak lari yang melibatkan menantu Munjidah Wahab –perempuan berdarah biru asal pesantren Tambaberas yang kala itu menjabat wakil bupati; penyelesaian dugaan korupsi dana pembangunan kolam renang internasional di Pesantren Tambakberas, dan kekerasan (pencambukan) terhadap santri yang terjadi di pesantren Urwatul Wutsqo. Kasus keempat, barangkali yang paling menggemparkan, adalah peristiwa kekerasan seksual yang melibatkan, Mochamad Subchi Azal Tsani (MSAT), salah satu putra kiai sangat berpengaruh di Ploso Jombang. Meski sudah ditetapkan sebagau tersangka sejak lama, kepolisian Jawa Timur belum pernah sekalipun berhasil meminta keterangannya. Hingga saat ini kasus MSAT masih terkatung-katung di Polda Jawa Timur.
PESANTREN GUNUNG ES KEKERASAN SEKSUAL?
Kasus MSAT adalah pintu masuk yang tepat bagi siapapun yang berkehendak baik untuk menyelamatkan wajah pesantren dari noda kekerasan seksual di lingkungannya. Wajah pesantren, jika diakui, telah dirusak dan dibopengi oleh praktek tercela, yang jumlah persisnya tidak ada yang tahu. Berapa persisnya jumlah kekerasan yang terjadi di pesantren selama kurun waktu 20 tahun terakhir ini? Sejujurnya, mungkin hanya Allah swt. yang tahu.
Saya harus akui tidak memiliki data akumulasi-kuantitatif yang bersifat pasti dan akurat terkait kekerasan seksual di institusi pendidikan Islam, termasuk pesantren. Keterbatasan sumber data pastilah menjadi halangan utama, selain bahwa menulis masalah ini membutuhkan nyali rangkap karena akan mengusik sebuah sistem yang dimiliki organisasi yang sangat kuat. Bahkan, sepanjang yang saya tahu, nstitusi sebesar Komisi Nasional Perlindungan Perempuan (Komnas Perempuan) –tempat muaranya pangkalan data kekerasan perempuan– tidak pernah berani menapis dan mempublikasikan kekerasan seksual berbasis institusi pendidikan agama — baik pesantren maupun yang lain.
Namun demikian, saya meyakini jumlah dan sebaran kekerasn seksual di pesantren tidaklah boleh diremehkan. Kekerasan seksual kerap terjadi pada anak di bawah umur dengan pelaku laki-laki dewasa. Sedangkan korbannya, tidak hanya terbatas anak perempuan namun juga laki-laki.
Saya sendiri pernah melakukan rapid assessment melalui media daring terkait masalah ini. Tahun 2012 Legal Resources Center untuk Keadilan Jender dan Hak Asasi Manusia (LCR-KJHAM), organisasi hak asasi manusia yang berkantor di Semarang, Jawa Tengah, mengeluarkan data yang mengagetkan. Menurut lembaga ini sedikitnya ada 100 santri putra dan putri menjadi korban kekerasan seksual selama kurun waktu 2011 di Jawa Tengah. Peristiwa ini teradi di beberapa pesantren di wilayah Wonogiri, Kota dan kabupaten Semarang, Klaten, Batang, Pati, Solo, Temanggung, dan Jepara. Menurut Fakhrurozi, direktur LCR KJHAM, pelakunya adalah para elit pesantren seperti kiai, guru spiritual, ustadz atau guru, pemimpin tariqat (mursid). “Di sebuah ponpes di Kota Semarang, sebanyak 26 santriwati dipaksa melakukan aborsi,” katanya seperti dilansir Solo Pos.
Jika gunungan kasus seperti ini terjadi di sebagian Jawa Tengah dalam kurun waktu setahun, adakah pihak yang berani menjamin peristiwa serupa tidak terjadi di provinsi lain? Di Jawa Timur, saya tidak dapa menemukan kompilasi data dari lembaga swadaya masyarakat maupun pemerintah. Data kekerasan terhadap perempuan dan anak yang biasa tersaji di institusi pelayanan terpadu kabupaten/kota tidak memilah secara tegas berdasarkan locus delicti pesantren dan non-pesantren. Saya masih merasa ketidakterpilahan ini bisa jadi dipicu kekuatiran dituding sebagai upaya mendeskriditkan pesantren –sebuah hal yang sangat ditakuti di wilayah Jawa Timur sebagai basis NU dan pesantren.
Namun demikian, saya melakukan pelacakan di dunia maya seputar kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di pesantren. Hasilnya, membuat hati saya semakin remuk redam. Di Pasuruan, saya menemukan beberapa santriwati dicabuli sejak tahun 2007. Kasusnya sendiri terbongkar delapan tahun kemudian . “Kalau nggak mau digituin, kamu santri laknat,” kata seorang korban di Pengadilan Negeri Bangil. Di Jember, polisi menangkap Ibrahim Kholil (38) karena menyetubuhi sekitar 11 santriwatinya. Bahkan menurut polisi ada seorang santriwati yang sudah setahun mengalami hal tersebut. Seorang pengurus pesantren di kawasan Dukuh Pakis Surabaya berinisial WG harus digelandang polisi. Ia dilaporkan salah satu orangtua yang tidak terima anaknya dicabuli selama 3 tahun sejak usia 14. Saya juga menemukan pencabulan terhadap santri/santriwati terjadi di banyak kabupaten/kota Jawa Timur, antara lain; Sampang, Sumenep, Gresik, Jombang, Mojokerto, Banyuwangi, Probolinggo, Lumajang, Sidoarjo, Bondowoso, Kediri, Blitar, Tulungagung, dan Jember.
MENGURAI PERSOALAN
Kekerasan seksual yang melibatkan pesantren di atas belum mencakup wilayah Jawa lainnya serta luar Pulau Jawa. Angkanya benar-benar tidak bisa disepelekan. Selama ini belum banyak yang mengurai faktor-faktor yang mendorong maraknya kasus kekerasan seksual di pesantren. Menurut saya, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk menghentikan, setidaknya meminimalkan, potensi terjadinya hal ini.
Pertama, faktor kultural. Pesantren, semodern apapun dirinya mengklaim, tetaplah merupakan institusi feodal dengan dua ciri unik yang selalu menyertainya; patriarkhis dan seksis. Ia membagi orang berdasarkan kelas tertentu –yang paling tampak adalah pembagian berdasarkan garis keturunan. Santri/santriwati yang memiliki orang tua dengan titel kiai atau pejabat biasanya mendapatkan perhatian lebih dari lingkungan. Pesantren juga sangat serius menjaga batas berdasarkan jenis kelamin, baik dalam arti substantif maupun interaktif, seraya meletakkan perempuan dalam posisi subordinat di hadapan laki-laki.
Kondisi ini merupakan konsekuensi logis mengingat literatur dominan yang dikaji dan dijadikan rujukan belum sepenuhnya ‘bersih’ dari cara pandang patriatkhis-misoginis, sungguhpun gerakan keadilan gender mulai banyak kita saksikan di beberapa tepat.
Bagi saya, apa yang kita makan, itulah yang membentuk kita. Santri dan kiai dibentuk oleh literatur. Literatur yang diajarkan pada santri/santriwati akan terefleksikan dalam sistem norma di pesantren dan sangat memengaruhi pembentukan karakter mereka. Sebagian besar kekerasan seksual di pesantren terjadi karena penyalahgunaan kewenangan (abuse of power) dari kelompok/individu yang lebih superior, misalnya kiai, ustadz, santri senior, pemimpin tarikat dan lain-lain. Korban merasa tidak memiliki kekuatan saat pelaku menggunakan ancaman maupun bujuk rayu yang bersifat agamis. Korban “dipaksa,” tunduk karena melawan berarti ia dianggap sedang melakukan kejahatan serius. Melawan perintah kiai adalah hal yang sangat nista di kalangan pesantren. Cara pandang ini sangat mungkin signifikan dipengaruhi oleh buku standart etika pembelajaran santri-kiai yang masih setia diajarkan di pesantren.
Santri/wati seperti dikunci oleh ketertundukan kepada siapapun yang dianggap guru dan senior. Kelompok kedua ini sangat sadar memiliki privilege namun sayangnya tidak diimbangi oleh ajaran/doktrin yang mewajibkan mereka untuk tidak terjatuh dalam abuse of power. Saat mereka terjatuh dalam kejahatan seksualitas –atau kejahatan yang lain, misalnya korupsi, maka berlakulah ajaran yang juga secara massif dijejalkan di kalangan pesantren, yakni ajaran tentang keutamaan menutup aib seseorang –apalagi aib seorang kiai– ketimbang menuntut keadilan.
Secara lebih luas dan mencengangkan, konsep menutup aib ini juga beroperasi di beberapa kalangan antarpesantren, terutama pesantren yang memiliki relasi keilmuan dengannya, maupun karena relasi perkawinan. Misalnya, jika kiai di pesantren x melakukan kejahatan seksual terhadap orang lain maka pesantren-pesantren yang dipimpin oleh kiai yang masih memiliki hubungan darah dengannya, atau dikelola oleh kiai yang pernah nyantri di pesantren tersebut, maka pesantren yang mereka pimpin akan berusaha menutupi kasusnya, alih-alih mendukung kasus tersebut bisa dituntaskan.
Yang lebih parah lagi, tidak jarang, pesantren-pesantren terlihat tidak merasa perlu menyuarakan keberpihakan kepada santri pesantren lain. Sangat mungkin karena dua hal; para santri tidak dididik dengan solidaritas sesama pelajar pesantren, atau yang lebih menyedihkan, otoritas pesantren merasa kritikannya atas pesantren lain atas kasus ini dianggap menyalahi fatsoen atau code of conduct antarpesantren.
Situasi sosiologis relasi santri/wati-kiai-pesantren seperti ini juga diperparah oleh kuatnya paradigma patriarkhi-misogini di banyak pesantren, sebagaimana saya singgung di atas. Hampir seluruh literatur hukum islam (fiqh) yang diajarkan di pesantren memposisikan perempuan sebagai individu yang tidak hanya inferior dibanding laki-laki, namun juga sebagai representasi faktor yang bisa menciptakan kekacauan, khususnya dalam masalah seksualitas. Kenyataan ini selanjutnya direspon dengan cara menerapkan “proteksi” berlebihan kepada perempuan. Namun sayangnya, alih-alih mendewasakan dan mendongkrak konfidensi perempuan, proteksi ini justru malah menindas perempuan dalam keminderan diri. Politik segregasi ketat berbasis jenis kelamin serta kebijakan merestriksi ketubuhan perempuan, salah satunya melalui politik berbusana, berdampak signifikan terhadap kedirian perempuan.
Di banyak pesantren, tidak hanya tubuh perempuan yang dianggap aurat namun juga termasuk suaranya. Banyak pesantren terasa menanggung beban dan obsesi untuk mampu menelurkan santriwati ideal. Idealitas ini bisa jadi tidak diukur berdasarkan kecerdasan emosional atau konfidensi dan kedewasaan dalam meneguhkan dirinya.
Alih-alih, idealitas santriwati adalah ia yang penurut, bisa melantunkan alquran dengan fasih, menunduk wajah, dan tidak bersikap kritis pada otoritas di luar dirinya. Padahal kita tahu, semakin perempuan tidak memiliki konfidensi terhadap dirinya sendiri, semakin mudah ia akan terjerembab dalam praktek kekerasan seksual yang memanfaatkan relasi kuasa yang timpang.
Faktor kedua, persoalan struktural yang melibatkan pesantren dengan suprastruktur yang ada di atasnya, yakni pemerintah/negara. Seperti dimaklumi, posisi politik pesantren, khususnya, selama pemerintahan Jokowi, semakin menguat. Hal ini salah satunya ditandai oleh pencanangan Hari Santri dan selanjutnya pengesahan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren. Dengan demikian, hal ini ini seperti membuat posisi pesantren tidak hanya kuat secara politik namun juga hukum. Pesantren yang saya anggap mirip seperti “negara dalam negara” membuat Pemerintah tampak rikuh dan perlu ekstra hati-hati berelasi untuk menyelesaikan masalah ini.
Dua faktor ini, saya kira, merupakan kunci menciptakan masa depan yang lebih baik agar kekeraan seksual, atau bahkan dalam skala yang lebih luas; gender maintreaming, menjadi lebih konkrit perwujudannya.
MERETAS MASA DEPAN
Saya memperkirakan ada puluhan juta santri/wati yang sedang menuntut ilmu di 27.000an pesantren di Indonesia. Fakta kekerasan seksual terhadap banyak dari mereka yang melibatkan otoritas elit pesantren merupakan hal yang tidak dikehendaki oleh siapapun, kecuali orang tidak waras. Berdasarkan pemaparan di atas, saya merasa perlu menyampaikan setidaknya dua hal yang barangkali berguna untuk mengamputasi laju kekerasan seksual terhadap mereka.
Pertama, dalam aspek kultural, pesantren sangat membutuhkan pergeseran paradigma; dari patriarkhi-misogini ke emansipatoris-partisipatori. Ini berarti pesantren mulai perlu selektif memilah dan memilih kitab kuning yang layak-tidak layak diajarkan, dan bagaimana metode pengajarannya. Apa yang telah digagas oleh jaringan feminis Islam Indonesia yang tergabung dalam Konferensi Ulama Perempuan Perempuan (KUPI) merupakan modalitas yang sangat luarbiasa, khususnya sebagai teladan dan sumber pengetahuan alternatif untuk memperbaiki kurikulum.
Namun demikian, pergeseran ini, harus diakui, sangatlah berat karena akan meniscayakan refleksi serius, khususnya, atas privilege yang selama ini dinikmati otoritas banyak pesantren yang cenderung feodal. Selain Gus Dur, sebagaimana yang saya yakini, nampaknya belum banyak kiai siap menerima kenyataan ada santri/watinya, yang tidak hanya pintar, namun juga kritis terhadasistem yang telah membesarkannya selama ini.
Poin krusial lain yang juga sayang jika tidak diperhatikan adalah kesediaan pesantren untuk rendah hati memberi pelajaran penting bagi santri/wati seputar keadilan gender. ketubuhan dan seksualitas. Jika memungkinkan, bahkan pelajaran ini perlu diberikan saat orientasi masa penerimaan santri/wati baru. Saya membayangkan para santri/wati baru dilengkapi dengan pengetahuan dasar early warning system bagaimana bersikap ketika menghadapi potensi kekerasan seksual dari siapapun, baik selama di pesantren maupun saat kembali ke rumah.
Dalam konteks ini, pesantren juga perlu secara serius menggandeng banyak pihak untuk merealisasikannya. Pemerintah sendiri, melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah meluncurkan program pesantren ramah anak yang dapat diintegrasikan dalam kerangka penghapusan kekerasan seksual terhadap santri/wati. Untuk mengoptimalisasi kerja-kerja ini, kementerian ini, dengan dukungan dari banyak pihak, khususnya Partai Kebangkitan Bangsa dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, juga perlu melengkapi kerangka kerjanya dengan unit monitoring dan evaluasi yang emansipatoris dan partisipatif.
*Tulisan ini ditulis dan diterbitkan pertama kali oleh LKiS dan FORMUJERES (Front Santri Melawan Kekerasan Seksual) pada tahun 2021.